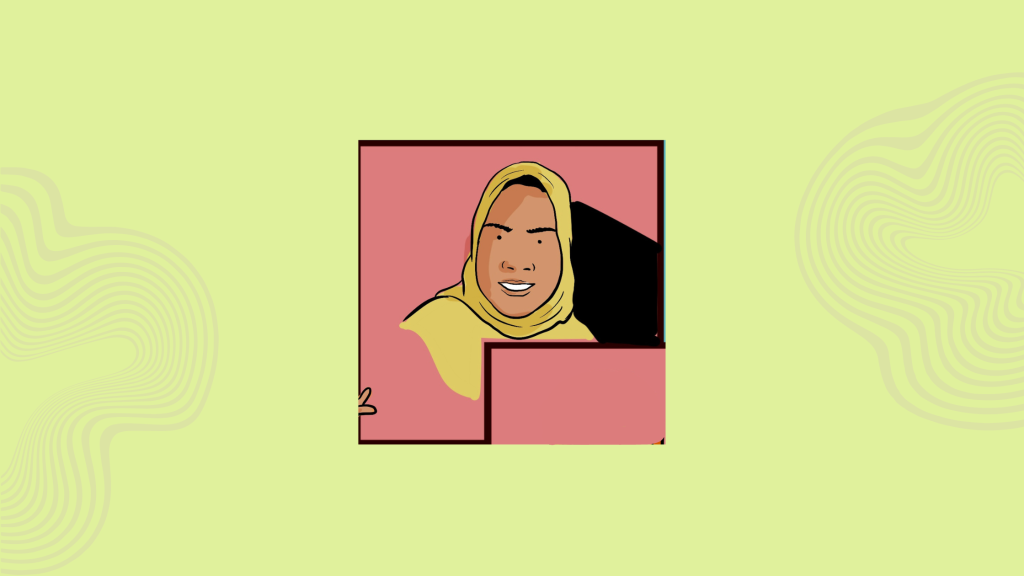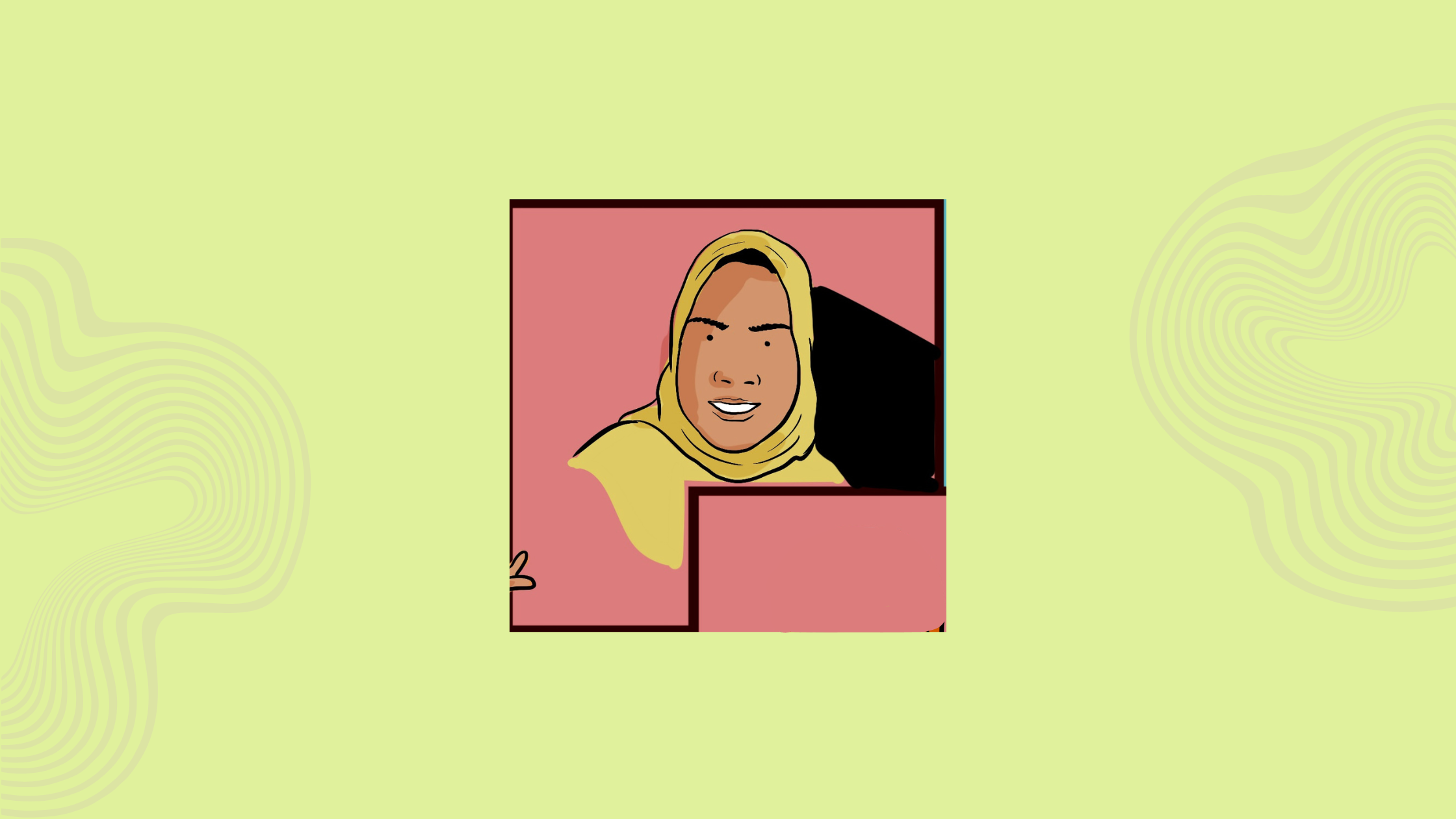“Gempanya kencang sekali, saya berpegangan di pintu, orang-orang sudah berlarian ke luar rumah. Saya tidak bisa lari keluar karena di rumah saya ada banyak orang termasuk anak saya yang berusia 1 tahun 6 bulan, korban pemerkosaan yang sedang hamil, serta beberapa mahasiswa yang sedang berada di rumah.” Dewi Rana Amir menceritakan detik-detik kejadian saat dirinya dan warga Sulawesi Tengah mengalami gempa yang terjadi pada tanggal 28 September 2018, di Kabupaten Donggala dan Kota Palu.
Tiba-tiba bergoyang dan sangat kencang.
Dewi Rana Amir merupakan direktur Yayasan Perkumpulan Lingkar Belajar untuk Perempuan Palu Sulawesi Tengah (LiBu Perempuan). LiBu Perempuan berfokus pada isu partisipasi perempuan dalam mencegah ekstremisme, tanggap krisis, serta pengurangan risiko bencana. Meskipun Dewi sendiri adalah korban gempa tsunami dan likuifaksi Palu, mau tidak mau dia juga harus menjadi relawan di tenda pengungsian.
Gempa tersebut menyebabkan tsunami yang mengakibatkan kerusakan parah di Bumi Tadulako dan sekitarnya. Gempa di Kota Palu memiliki kekuatan 7,4 skala richter dengan pusat gempa berada di kedalaman 10 km dan berjarak 27 km Timur Laut Donggala. Menurut data yang dikutip dari Detik.com, Badan Meteorologi Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan tsunami setelah terjadi gempa, namun tsunami setinggi enam meter akhirnya menghantam Kota Palu hanya beberapa menit setelah peringatan tersebut dikeluarkan.
Banyak masyarakat yang tidak punya waktu untuk menyelamatkan diri, dan jaringan komunikasi yang terputus sehingga membuat banyak orang tidak mengetahui adanya peringatan tsunami.
Setelah gempa dan tsunami, Kota Palu menghadapi fenomena alam lain, yaitu likuifaksi. Gempa mengakibatkan tanah kehilangan ikatannya dan tanah berpasir di sekitar laut menjadi likuifaksi, sehingga bangunan serta kendaraan yang berada di atasnya terangkat. Jumlah korban jiwa akibat gempa bumi, tsunami dan likuifaksi di Palu mencapai 4.338 jiwa, sementara korban hilang sebanyak 1.373 jiwa.
“Hari Jumat itu tidak biasanya saya pulang pukul 15.00 sore karena di hari yang sama sudah terjadi dua kali gempa sebelumnya. Ada firasat bahwa saya harus pulang,” kenang Dewi.
Dan benar saja pada pukul 17.00 gempa besar itu pun datang. Dewi tidak bisa meninggalkan rumah meskipun risiko besar mengancamnya, Ia malah masuk dan membantu orang-orang di rumahnya untuk keluar.
“Ada korban pemerkosaan yang sedang hamil, saya khawatir ia akan shock dan melahirkan. Rumah Aman sudah penuh saat itu, jadi ia ditampung di rumah saya.” tutur Dewi.
Beberapa hari setelah bencana, Dewi nekat pergi ke kota Palu untuk mencari makanan, susu, dan pampers karena persediaan di pengungsian sangat terbatas. Kota Palu saat itu terlihat seperti kota mati karena banyak terjadi penjarahan dan tidak ada toko yang buka. Situasi sangat kacau karena listrik dan jaringan telepon mati selama lebih dari seminggu.
“Keluarga memaksa saya untuk meninggalkan Palu, tapi saya tidak mau karena banyak orang yang harus dibantu. Akhirnya saya mengorganisir keluarga untuk membawakan air minum pampers dan susu.” ujar Dewi
Meskipun keluarganya memaksa Dewi untuk meninggalkan Palu, ia tetap bertahan dan membantu orang-orang yang membutuhkan bantuan. Ia juga mengidentifikasi staf di kantor LiBu untuk memastikan bahwa mereka selamat.
Bersama Menanggapi Kebutuhan Khusus Perempuan dalam Bencana
Tidak lama setelah bencana tersebut, Dewi dari LiBu Perempuan bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Sulteng segera merespon korban gempa, tsunami, dan likuifaksi dengan mendirikan tenda khusus ramah perempuan. “Kami membangun tenda besar untuk perempuan dengan ukuran sekitar 8x11m dan 6x10m di Kabupaten Donggala, Sigi, dan Parigi Moutong. Yang menarik dari tenda ini adalah kemudahan akses layanan informasi bagi penyintas, misalnya, ada ibu-ibu yang menangis karena kehilangan anaknya karena tertimbun likuifaksi.” jelas Dewi.
Dewi terkejut bahwa tenda khusus perempuan ini menjadi layanan yang sangat penting, tidak sekadar laporan kehilangan pasca bencana, tetapi juga para ibu hamil di tempat pengungsian dapat melaporkan diri dan dirujuk untuk pemeriksaan kesehatan. “Secara terjadwal kami masuk ke tenda-tenda sehingga kami memiliki data, misalnya ada 150 tenda, kami mencatat informasi seperti usia lansia yang tinggal di tenda nomor 1, dan jumlah remaja yang ada di sana. Data ini sangat penting untuk mengetahui bagaimana kondisi di dalam tenda. Sering kami temukan berbagai masalah yang tak terduga, misalnya terkait pakaian yang dikenakan oleh gadis remaja yang menarik perhatian laki-laki di pengungsian. Misalnya, mereka memakai celana pendek sebagai pakaian rumah sehari-hari karena mereka tidak sempat membawa baju saat gempa terjadi. Maka remaja putri ini kami berikan tempat tidur di tenda perempuan bersama dengan kelompok rentan lainnya”. ujar Dewi
Ini adalah bencana pertama yang sangat besar bagi Dewi dan warga sehingga mereka harus mengungsi. Maka ini menjadi kali pertama juga bagi mereka dalam mengembangkan mekanisme bencana seperti bagaimana menyusun daftar kebutuhan spesifik untuk perempuan, melakukan pendataan pengungsi, menangani laporan korban, dan bahkan mendirikan tenda khusus perempuan.
“Sebelumnya, Sulteng pernah mengalami beberapa gempa tapi tidak sampai mengungsi. Aturan dan mekanisme yang mendesak harus dibuat melihat kondisi satu tenda bisa menampung 20-27 kepala keluarga. Situasi ini sangat rentan untuk kelompok perempuan, terutama gadis remaja apalagi mereka sudah tidak punya keluarga lagi akibat bencana tersebut”. jelas Dewi
Dewi menjelaskan akan ada potensi Kekerasan Berbasis Gender (KBG) pada situasi ini. LiBu, yang menangani 3-4 kasus KBG setiap harinya, memiliki pengalaman yang sangat berguna untuk penanganan KBG di tempat pengungsian. “Tiap harinya, banyak laporan KBG di pengungsian, termasuk laporan pemerkosaan yang pelakunya bapak tiri, korban berusia 16 tahun bahkan sampai hamil. Selain itu, ada juga laporan percobaan pemerkosaan, pengintipan, merekam toilet perempuan dengan HP, serta masalah lain seperti gangguan kesehatan reproduksi akibat air yang tidak bersih, dan kasus-kasus depresi di pengungsian.” ungkap Dewi
Menjadi Relawan yang Tak Kenal Lelah
Dewi Rana dan beberapa korban bencana lainnya dengan penuh semangat menjadi relawan, meskipun mereka masih dalam kondisi berduka dan mengalami sakit. Semangat mereka untuk membantu pemulihan korban lainnya menjadi keharuan tersendiri. “Satu tenda ditangani oleh 5 orang relawan, sebagian besar dari mereka adalah para korban bencana itu juga,” cerita Dewi.
Para relawan ini tidak kenal lelah dan tidak memperdulikan rasa sakit. Ada yang kepalanya masih dijahit, namun tetap ingin menjadi relawan, termasuk korban tsunami dan bahkan korban perkosaan yang dengan bersemangat mengajukan diri menjadi relawan. “Kami sangat sibuk sampai lupa bersedih.” kenang Dewi. Sekarang para relawan tetap saling berkumpul untuk menjalin silaturahmi hingga saat ini. Banyak pelajaran yang diperoleh dari pengalaman menghadapi situasi bencana di pengungsian, yang kemudian mendorong mereka untuk tumbuh dan bahkan menjadi pemimpin di desa mereka. “Saya bersyukur melihat mantan relawan bencana maju menjadi pemimpin mencalonkan diri menjadi kepala desa. Mereka menerapkan pengalaman saat menjadi relawan di desa dan sering dimintai pandangan untuk berbicara dalam pertemuan tingkat desa.” ujar Dewi
Para korban bencana sebelumnya memiliki latar belakang profesi yang beragam, seperti petani, pedagang, buruh tani, dan PNS. Banyak dari mereka mengalami kehilangan pekerjaan dan sumber penghasilan. Hal ini tentunya menimbulkan rasa frustasi pasca bencana. Mereka kehilangan semuanya, rumah-rumah mereka hancur, dan beberapa desa bahkan mengalami likuifaksi.
Selama dua tahun setelah bencana, para relawan masih mengirim makanan siap saji ke Huntara (Hunian Sementara) untuk penduduk dari Sibalaya Selatan ini karena mereka tidak punya pilihan selain tinggal di Huntara dan menunggu bantuan akibat tidak ada lagi sawah yang bisa digarap. Keadaan semakin memburuk setelah munculnya pandemic Covid-19. Banyak ibu-ibu yang merasa frustasi bahkan ingin menyerahkan anaknya untuk diadopsi. “Kalau saya dipukul suami, atau tidak makan, saya sudah biasa. Tapi kalau anak saya tidak bisa makan, saya tidak sanggup melihatnya, kami bingung mau bekerja apa, tolong adopsi saja anak saya.” Ujar salah seorang korban. Dewi yang mendengar hal itu menjawab “Pengasuhan terbaik bagi anak tetap berada di tangan orang tua, jangan sampai menyerahkannya untuk adopsi, kami akan membantu dengan memberikan suplai susu, beras, dan gula. Saya bahkan sampai menulis surat kepada anggota DPR RI untuk minta bantuan dan diberi 40 juta rupiah untuk dibelikan sembako.” ujarnya
Bangkit dan Memulai Hidup Pasca Bencana
Para korban yang selamat dari bencana juga harus bangkit dari keterpurukan karena mereka telah kehilangan segalanya, termasuk pekerjaan. Situasi ini mendorong banyak dari mereka yang merantau. “Banyak warga terpaksa merantau, seperti ke Kalimantan, karena sudah tidak ada yang bisa dikerjakan di sini. Hal ini juga sering menjadi motif KDRT, di mana suami tidak tahan tinggal diam di pengungsian dan Huntara. Mereka tidak terbiasa tinggal di rumah seperti perempuan dan memilih untuk pergi bahkan tidak kembali. Perempuan cenderung lebih kuat dalam menghadapi situasi bencana dan lebih mampu bertahan. Terdapat sekitar 35 orang suami yang pergi dan tidak kembali, akhirnya mereka malah menikah lagi dengan perempuan di tempat lain dan bercerai. Kasus KDRT sering sekali terjadi di pengungsian dan Huntara, bahkan karena hal sepele seperti arah kipas angin saja bisa menyebabkan pemukulan terhadap istri.” ujar Dewi
Kepentingan Perempuan Akhirnya Menjadi Perhatian dan Masuk dalam Regulasi
“Saya sangat senang karena dalam rapat Perda yang terakhir, semua sudah mulai bicara soal kerentanan perempuan. Mulai dari Dinas Pekerjaan Umum (PU), sampai BMKG, mereka telah memahami kompleksitas kerentanan yang dialami perempuan. Peraturan yang dibuat terkait kerentanan perempuan bahkan telah direplikasi dalam bentuk ruang ramah perempuan di Masamba dan Manado pada saat terjadi bencana banjir.” ungkap Dewi
“setiap hari Kamis jam 10.00 pagi, kami secara rutin mengadakan rapat di cluster untuk mendengarkan persoalan yang dihadapi para pemangku kepentingan. Hal-hal seperti kebutuhan air bersih, perbaikan toilet, dan berbagai isu lainnya dibahas dalam rapat tersebut, dan tanggapan cepat diberikan untuk menangani masalah-masalah tersebut. Dalam rapat itu kami juga membahas bagaimana mendokumentasikan data dan mengkategorikan jenis-jenis kasus yang terjadi. Hal ini sangat penting untuk menentukan kebutuhan yang harus disiapkan. Dalam seminggu rata-rata terdapat 4 kasus pelecehan, perkawinan anak, kekerasan aparat dan kasus pengintipan. Data ini berharga untuk pembuatan regulasi di tingkat daerah dan dapat mengubah pandangan para stakeholder.” Ujar Dewi
Peraturan Daerah (Perda) Penanggulangan Bencana di Sulawesi Tenggara kini telah mengakomodasi isu kelompok rentan melalui penyediaan ruang ramah perempuan. Perda Penanggulangan Bencana ini juga sudah diimplementasikan dalam Peraturan Gubernur. Dalam 72 jam pertama setelah terjadi bencana, bantuan harus mencakup kebutuhan spesifik perempuan dan mekanisme penanganan bencana. Hal ini juga mencakup advokasi rencana aksi daerah untuk rehabilitasi dan rekonstruksi, di mana perempuan dan kelompok rentan memiliki hak untuk didengarkan. Salah satu keberhasilan yang terlihat adalah melalui Inpres Percepatan Pembangunan Sulawesi Tenggara Nomor 10 tahun 2018 yang telah memasukkan isu perlindungan perempuan dan anak.
Para Pendamping Korban Kekerasan Juga Butuh Dukungan
Dewi dan rekan-rekan di LiBu Perempuan membawa pengalaman mereka dalam mendampingi kasus kekerasan terhadap perempuan, yang kemudian dapat diterapkan dalam siituasi konflik dan bencana. Tugas ini tentu tidaklah mudah, dan para perempuan pembela HAM ini membutuhkan dukungan khusus, terutama dalam hal kesehatan mental. “Untuk menangani masalah kesehatan mental, di LiBu kami menyediakan ruang berbagi dengan psikolog setiap malam Rabu yang siap memberikan konsultasi psikososial. LiBu juga punya skema ruang aman yang tersedia.” ujar Dewi
Dalam tugas sehari-harinya sebagai pendamping korban kekerasan, Dewi menyatakan bahwa penanganan kasus kekerasan seksual berbeda-beda dalam setiap situasinya, tergantung pada ketangguhan, keputusan, dan pilihan korban. “Sebagai pendamping, tugas kita hanya memberi pilihan, terkadang ada korban yang menolak untuk melanjutkan proses hukum dan memilih menghormati orang tuanya serta berdamai dengan pelaku. Meskipun sebenarnya kekerasan seksual tidak boleh diselesaikan di luar sistem peradilan, namun terkadang korban memilih untuk tidak melaporkan kasusnya, tidak apa-apa, itu adalah bagian dari proses belajar. Mengingat batapa sulitnya bagi korban untuk bangkit setelah mengalami kejadian tersebut.” ujar Dewi,
Menurut Dewi, selama ini perempuan hanya meminta untuk didengar dan memiliki ruang untuk berbicara, tetapi seringkali tidak ada yang mendukung di rumahnya. “Di LiBu, kami memiliki prinsip untuk bagaimana mendengarkan dengan baik. Hal ini mengesankan bahwa ketika perempuan diberi kesempatan untuk berbicara dan didengar, ternyata itu dapat memberikan bantuan hanya melalui memberikan dukungan. Para korban mengatakan bahwa mereka merasa dihargai dan menjadi manusia baru serta mampu menghadapi segala hal dengan kekuatan. Mereka hanya membutuhkan teman untuk berbagi.” Ujar Dewi
Dewi menyarankan agar dalam situasi bencana dan konflik, segera dibuat mekanisme yang dapat dengan mudah diakses oleh semua semua, sekecil apapun itu. Misalnya, dengan menciptakan sistem referal sederhana yang melibatkan komponen psikososial dan bantuan hukum. “Saya ingin menyampaikan pesan kepada pemerintah untuk memperhatikan kebutuhan perempuan dalam 72 jam pertama dan memberikan bantuan yang spesifik untuk mereka. Masalah seperti menstruasi dan persalinan tidak bisa ditunda. Perempuan seringkali tidak memiliki akses untuk mengganti pembalut karena kurangnya bantuan yang tersedia.” Ungkap Dewi
Ia juga berharap agar perempuan lebih banyak didengar dalam situasi bencana. Para perempuan memiliki kepekaan yang tinggi terhadap gempa dan dapat mengamati reaksi binatang yang gelisah yang diyakini dapat mendeteksi bencana. Hal ini merupakan pengetahuan lokal yang dimiliki perempuan. Pengetahuan ini memiliki potensi untuk menyelamatkan nyawa, karena tsunami dapat terdeteksi sejak dini. Terbukti dari sejarah bencana menunjukkan bahwa beberapa desa diberi nama sesuai dengan unsur-unsur bencana. Sebagai contoh, desa ‘Rogo’ yang berarti ‘hancur’ dan Desa ‘Beka’ yang berarti ‘terbelah’. Orang tua zaman dulu memberikan nama-nama desa ini sebagai pengingat bagi keturunan mereka agar selalu waspada.