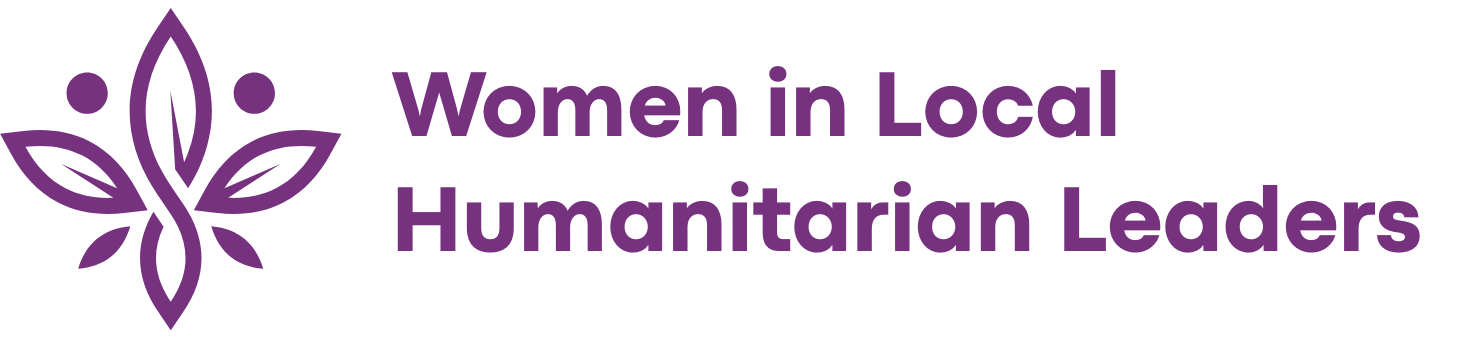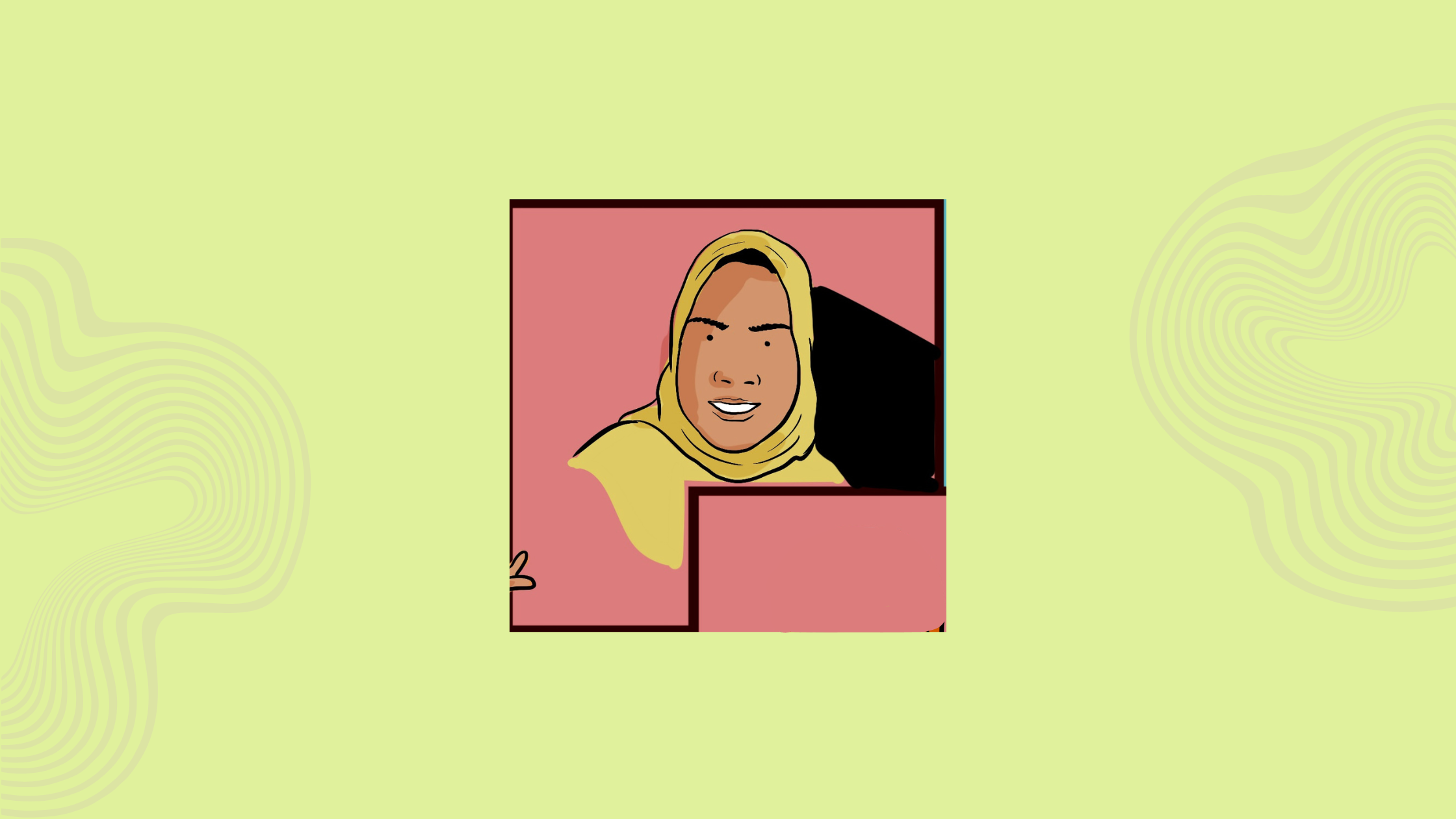Ambon 1999, Konflik Pecah
Hidup di kamp pengungsian tak pernah dibayangkan oleh Baihajar Tualeka. Namun, realita ini harus dia hadapi setelah rumah dan kampungnya terbakar.
Kehidupan di kamp pengungsian sangatlah sulit. Tidak ada privasi, tidak ada sarana umum, dan situasinya serba terbatas. Kadang-kadang, ia dan perempuan lainnya tidak menggunakan pakaian dalam karena tidak ada yang dapat dipakai. Kondisinya semakin memburuk saat menstruasi, mereka harus merobek handuk untuk digunakan sebagai pembalut. Belum lagi harus menghadapi antrian panjang di kamar mandi yang kadang-kadang membuat mereka enggan untuk mandi. Situasi ini tidak pernah terbayangkan sebelumnya sekaligus juga tidak tertahankan.
Orang-orang tidur di lantai beralaskan kardus atau tikar. Anak-anak tak bisa mendapatkan pendidikan. Wajah-wajah yang terlihat depresi dan trauma menjadi pemandangan di mana-mana.
“Anak-anak juga tidak dapat berinteraksi. Sementara itu, ibu-ibu juga tampak mengalami depresi. Mereka tidak memiliki pekerjaan dan tidak ada aktivitas yang dapat memberikan mereka penghasilan.” tutur Baihajar yang akrab disapa Bai.
Situasi ini membuat mereka hidup bergantung pada bantuan dari berbagai pihak, seperti organisasi internasional, pemerintah, dan organisasi keagamaan.
Kondisi ini bermula dari pertikaian antara dua geng pemuda di Pasar Mardika Ambon pada bulan pertama tahun tersebut. Pertikaian dengan cepat meluas menjadi konflik antar agama setelah terjadinya pembakaran masjid dan gereja. Dua komunitas, yaitu Islam dan Kristen, saling menyerang. Rumah ibadah dan pemukiman pun dibakar, masing-masing saling bunuh dan saling tembak. Tindakan kekerasan dan penjarahan juga terjadi di berbagai tempat.
Sementara di masa lalu, Ambon Maluku dikenal sebagai negeri yang damai. Ada tradisi ‘pela gandong’ yang menempatkan persaudaraan sebagai keutamaan. Negeri Islam dan negeri Kristen hidup toleran dan harmonis. Tenggang rasa, saling menyayangi dan tolong-menolong menjadi nilai yang mendasari kehidupan bersama.
Situasi yang berbalik 180 derajat ini memunculkan dugaan bahwa konflik Ambon adalah hasil rekayasa terkait perebutan kekuasaan pasca Orde Baru. Sebagaimana yang terjadi di Sambas, Kalimantan Barat dan Sampit, Kalimantan Tengah.
Bai menjelang usia 25 tahun, belum lama jadi sarjana dan baru saja merintis usaha pertanian. Konflik merajalela hingga ke seluruh pelosok Maluku. Desa binaan yang ia dampingi ikut terbakar dan hancur. Mimpinya untuk memberdayakan petani cokelat menjadi sirna.
Di tengah kekacauan dan ketidakpastian tersebut, Bai berpikir tentang apa yang bisa dilakukan agar orang-orang memiliki aktivitas dan merasa bahagia. “Meskipun mereka hidup di situasi yang sulit seperti ini, mereka dapat memiliki pendapatan, atau terlibat dalam aktivitas yang dapat membantu pemulihan mereka.” ujarnya.
Bai kemudian memfokuskan diri pada pendampingan anak-anak dan perempuan, karena menurutnya mereka merupakan kelompok yang sangat rentan terdampak oleh kekerasan yang terjadi. Dalam situasi sulit tersebut, angka kekerasan terhadap perempuan sangat tinggi. Anak-anak juga menjadi korban kekerasan seksual.
Ketika memulai pendampingan pada 1999-2000, Bai mengaku tidak memiliki keterampilan dan sumber daya yang sangat terbatas. Namun, kondisi ini tidak menyurutkan semangat Bai, anak kelima dari sembilan bersaudara tersebut.
“Jadi, kita hanya mengajak anak-anak ini untuk bermain dan belajar. Kita juga tidak memiliki tempat, jadi kami duduknya di bawah pohon. Kadang-kadang, kalau ada halaman yang kosong, kami dapat bermain di sana. Karena yang terpenting adalah membuat anak-anak ini bahagia, gembira, dan mengalihkan perhatian mereka dari situasi yang penuh dengan kekerasan. Supaya anak-anak juga memiliki aktivitas dan dapat kembali belajar,” terangnya.
Perempuan yang menghabiskan masa kecilnya di Papua ini juga mendirikan taman baca. Buku-buku diperoleh dari donasi. Setiap hari Jumat, anak-anak berkumpul dan belajar bersama. Jumlah anak-anak yang berusia di bawah 18 tahun pada waktu itu sangat banyak, sekitar 600 anak sehingga dibuat sistem bergilir (sif).
Sementara untuk ibu-ibu, Bai menggunakan pendekatan psikososial yang diintegrasikan dengan pemberdayaan ekonomi. Pada awalnya, ia hanya mengorganisir 20 perempuan yang diberikan modal sebesar 300 ribu. Mereka menggunakan modal tersebut untuk berjualan, sehingga mereka memiliki pendapatan dan aktivitas di tengah situasi yang sulit.
Modal tersebut diperoleh dari sumbangan orang-orang dan hasil menyisihkan keuntungan yang diperolehnya selama berjualan. Bai sempat berjualan atau mengasong di atas kapal dan membuka warung. Ia mengelola modal tersebut dengan sistem bergulir.
“Jadi, sistem bergulir diberikan kepada mereka, misalnya Ibu A mendapatkan sejumlah tertentu, Ibu B mendapatkan sejumlah tertentu. Kemudian, mereka membayarnya secara bulanan. Setelah uangnya terkumpul cukup, kita memberikan kepada orang lain. Jadi, sistemnya berputar,” ujarnya.
Para ibu yang mendapatkan modal membuka kios-kios kecil di pinggir kamp dengan menjual minuman. Ada juga yang menjadi papalele, berjualan ikan, atau sayuran keliling.
Akhirnya, para ibu itu merasa dengan memiliki aktivitas, mereka mulai memiliki harapan hidup yang baru. Mereka mulai menata kembali kondisi ekonomi mereka, meskipun pendapatan mereka masih terbatas dibandingkan dengan kondisi sebelum konflik terjadi. Karena rata-rata para ibu ini rumahnya hancur dan tidak memiliki apa-apa karena kehilangan harta benda. Ketika mengungsi, mereka tidak dapat membawa apapun karena situasinya sangat cepat, sehingga hanya bisa menyelamatkan diri saja.
Aktivitas Bai berjualan di atas kapal dan mengorganisir perempuan cukup berisiko, nyawa bisa menjadi taruhan. Untungnya, Bai mendapat dukungan dari keluarganya. Orang tuanya memberikan pesan agar ia menjaga dirnya dengan baik, mengingat bahwa bekerja dalam situasi seperti ini harus dilakukan dengan hati-hati. Pesan ibunya selalu diingat, “Kalau misalkan terjadi sesuatu, orang yang akan merasa kehilangan itu saya sebagai ibu yang telah membesarkan dan melahirkan kamu.” ujarnya.
Keberhasilan Bai mengajak ibu-ibu untuk beraktivitas dan menguatkan ekonomi mereka tidak selalu berjalan lancar. Ada ibu-ibu yang dilarang suaminya untuk mengikuti kegiatan tersebut dengan menyebarkan isu-isu yang membatasi perempuan dalam berinteraksi. Muncul tudingan bahwa kegiatan tersebut memiliki kepentingan agama tertentu. Suara-suara miring yang beredar misalnya, “Jangan terlibat kegiatan begitu karena nanti membawa misi-misi bagi agama-agama tertentu.” Ujar Bai.
Pelarangan tersebut juga berkaitan dengan anggapan bahwa upaya damai yang dilakukan oleh ibu-ibu dianggap untuk kepentingan agama tertentu. Pada saat itu, meskipun aksi saling serang antar komunitas telah berhenti, situasinya belum dapat disebut damai karena keadilan masih belum ditegakkan. Bai bersama beberapa temannya kemudian mencoba menghidupkan pasar tradisional, bertransaksi sayuran dengan komunitas lain. Beberapa ibu juga yang mulai menjadi papalele. Dari sinilah proses perdamaian secara alamiah berawal, melalui kegiatan ekonomi perempuan di akar rumput.
Adanya larangan ini kadang membuat para ibu merasa ketakutan. Menghadapi situasi semacam ini, Bai memilih untuk tetap fokus pada kegiatan rutin yang dilakukan bersama ibu-ibu dan anak-anak. Meskipun ada penolakan, ibu-ibu ini terus ikut terlibat. Setelah mengikuti kegiatan, mereka menyampaikan kepada para suaminya tentang segala hal yang telah dilakukan, termasuk peningkatan kapasitas dan penguatan yang mereka peroleh. Ibu-ibu merasa mendapat manfaat karena mereka memiliki perencanaan masa depan dan mengetahui pola asuh anak yang baik dalam situasi konflik. Pendekatan ini dapat membuat para suami akhirnya mendukung dan tidak lagi melarang istri mereka terlibat dalam kegiatan tersebut.
“Kita tidak menanggapi tantangan-tantangan tersebut dengan cara yang menyakiti orang-orang. Sebaliknya, kita menunjukkan melalui aktivitas-aktivitas yang memberikan dampak positif bagi ibu-ibu dan bagi anak-anak itu sendiri. Kami juga mengintegrasikannya dengan pemulihan dan pemberdayaan ekonomi para ibu,” tuturnya.
Bai juga mengajar ibu-ibu yang tidak bisa membaca dan menulis untuk mengenali huruf, berlatih membaca, dan menulis. Dengan begitu mereka tidak mudah tertipu dan tidak menjadi korban. Di kamp pengungsi, kelompok lansia dan perempuan kepala keluarga mengalami kesulitan dalam mendapatkan akses informasi. Terlebih lagi, latar belakang pendidikan para ibu tersebut juga beragam. Oleh karena itu, Bai selalu memberikan informasi apapun yang diperlukan kepada mereka, seperti persyaratan untuk mendapatkan bantuan dan relokasi, dan hal-hal sejenis.
Dengan kemampuan baca tulis ini, para perempuan memiliki posisi tawar yang lebih kuat dalam berinteraksi dengan pemerintah. Seperti misalnya saat mereka berurusan dengan Dinas Sosial untuk keperluan relokasi. Hingga akhirnya mereka dapat memperoleh hak-hak mereka sebagai pengungsi.
“Misalnya, jika mereka ingin direlokasi ke tempat A, apa saja persyaratannya. Kemudian, setiap individu harus mendapatkan jatah Hidup (Jadup). Setiap anggota keluarga diberikan fasilitas sebesar 500 ribu rupiah, sehingga jika ada 5 orang totalnya adalah 2,5 juta rupiah. Namun, pada saat itu terjadi banyak sekali pemotongan yang dilakukan oleh para calo, sehingga banyak orang yang tidak memperoleh haknya. Keberadaan banyak calo ini juga sangat merugikan para ibu sebagai pengungsi” jelasnya.
Kondisi di kamp juga menjadi perhatian utama bagi Bai, terutama kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan kekerasan seksual yang tinggi. Melalui LAPPAN, organisasi yang didirikannya pada tahun 2002 dengan fokus kerja pada isu perempuan dan anak, Bai aktif menangani dan memberikan pendampingan dalam kasus-kasus tersebut.
Bai mengingat salah satu momen penting ketika pemerintah pusat mengesahkan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) pada tahun 2004. Perempuan di Ambon merespons pengesahan UU tersebut dengan mengadakan long march di sekitar kota Ambon.
Kegembiraan meluap karena saat itu angka KDRT di kamp pengungsian sangat tinggi. Ibu-ibu merasa senang dan bahagia dengan adanya produk hukum yang melindungi perempuan. Bagi mereka keberadaan UU ini menegaskan bahwa persoalan rumah tangga seperti kekerasan telah menjadi persoalan publik. Oleh karena itu, perempuan tidak boleh lagi bungkam atau diam, harus mulai berani bicara. Tidak perlu merasa KDRT adalah aib.
Ada cerita menarik tentang keterlibatan anak-anak dalam pencegahan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Salah satu Ibu yang berjualan asongan di atas kapal untuk mencukupi kebutuhan 8 orang anaknya. Sementara itu, suaminya bekerja sebagai tukang becak dan seringkali terjerumus dalam kebiasaan minum-minuman keras. Jika suami pulang dan tidak menemukan makanan yang disiapkan di atas meja, ia akan marah dan membuang semua barang yang ada di rumah. Sang ibu merasa bahwa mereka harus bekerja keras untuk mendapatkan barang-barang tersebut. Meskipun pendapatannya hanya sekitar 20 ribu per hari, kadang bahkan hanya 5 ribu, ia harus tetap mencukupi kebutuhan delapan anaknya.
Anak yang tertua menyaksikan penderitaan yang dialami ibunya. Kadang-kadang, saat mereka pulang sekolah, wajah ibunya sudah lebam. Meskipun Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) telah disahkan, ibu dan suaminya tidak bisa membaca. Oleh karena itu, anak-anak tersebut menempelkan salinan undang-undang tersebut di dinding rumah yang terbuat dari tripleks. Karena mereka tidak memiliki uang untuk beli lem, mereka menggunakan nasi sebagai perekatnya. Pada tahun 2005, para pengungsi akhirnya direlokasi, sehingga mereka tidak lagi tinggal di kamp pengungsian.
Setelah itu mereka membacakannya dengan keras agar bapak mereka yang tidak bisa membaca dapat mengetahui isi UU tersebut. Mereka membacakan pasal 44 yang menyebutkan bahwa pelaku kekerasan terhadap istri dan anak di dalam rumah tangga dapat dijerat pidana penjara paling lama 15 tahun. “Siapapun yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga bisa dijerat. Jadi, jika bapak memukuli mama lagi, dan mama melaporkannya, bapak bisa dipenjara,” ucap sang anak. Mendengar hal tersebut, bapak mereka menjadi ketakutan.
ibu tersebut yang tinggal di dekat kantor LAPPAN (Lembaga Pemberdayaan Perempuan dan Anak) mengungkapkan bahwa sejak saat itu suaminya tidak lagi melakukan kekerasan. Akhirnya anak-anak mereka bisa tumbuh dengan baik dan mendapatkan pendidikan hingga sarjana dan memiliki pekerjaan yang layak.
“Untunglah saya tidak terus-menerus melakukan KDRT. Jika tidak diberitahu oleh anak saya tentang UU PKDRT yang ditempel di dinding rumah kami, saya tidak akan tahu. Akhirnya, saya mengubah perilaku saya dan bisa menyelamatkan keluarga saya menuju kehidupan yang lebih baik. Ternyata kekerasan hanya membuat situasi semakin sulit dan kehidupan kami menjadi lebih buruk.” ujar si bapak seperti dituturkan Bai.
Selain KDRT, kasus kekerasan seksual di kamp pengungsian juga sangat tinggi. Ketika seorang anak mengalami pemerkosaan, seringkali orang tuanya merasa malu dan pergi meninggalkan kamp karena diancam pelaku. Beberapa korban juga mengalami kehamilan sebagai akibat dari kekerasan tersebut.Sayangnya, dalam beberapa kasus, korban tidak mendapatkan pendampingan karena keluarganya sudah pergi. Bahkan, ada kasus di mana anak-anak yang mengalami pemerkosaan justru disalahkan dan dianggap sebagai penyebab terjadinya kekerasan oleh keluarganya. Masyarakat di kamp juga memberikan stigma kepada korban, menyebabkan korban dan keluarganya merasa malu dan akhirnya memilih pergi meninggalkan tempat tersebut.
Melihat kondisi tersebut, Bai kemudian melakukan upaya penguatan kepada ibu-ibu dan pencegahan agar kekerasan seksual tidak terus terjadi di dalam kamp. Salah satu upaya tersebut adalah memberikan dukungan kepada korban melalui penguatan komunitas. Bai mengajak seluruh komunitas untuk menunjukkan empati dan memberikan bantuan kepada korban dan keluarganya. Jika korban membutuhkan pendampingan untuk melaporkan kasusnya ke kepolisian, ibu-ibu pendamping akan mendampingi proses pelaporan tersebut.
“Saat itu, memang kita banyak mendampingi korban kekerasan seksual maupun korban kekerasan dalam rumah tangga. Sehingga ibu-ibu ini terus menyuarakan dan melakukan langkah-langkah pencegahan supaya kasus-kasus serupa tidak terulang.” ujarnya.
Bai mengakui bahwa melihat perubahan hasil atas penguatan kapasitas yang ia lakukan terhadap ibu-ibu yang didampinginya membutuhkan proses yang panjang. Mereka tinggal di kamp pengungsian mulai dari tahun 1999 hingga 2005, dan baru sekarang dampak perubahan tersebut dapat terlihat.
Awalnya, ibu-ibu itu pemalu, pendiam, tidak memiliki akses apa pun, merasa ketakutan saat berhadapan dengan berbagai pihak dan tidak bisa baca tulis. Namun, seiring waktu, mereka mengalami transformasi menjadi sosok yang mampu bernegosiasi dan menjadi pendamping bagi perempuan dan anak korban kekerasan di kamp masing-masing. Mereka juga mampu menyuarakan hak-hak mereka sebagai pengungsi.
Sementara itu, melalui proses pendampingan, anak-anak berhasil mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Bai dan LAPPAN juga memberikan beasiswa kepada mereka. LAPPAN, sebagai lembaga yang didirikannya, memiliki fokus pada pendidikan dan pemulihan. Bai yakin bahwa dengan pendidikan yang baik bagi anak-anak, akan menghasilkan generasi yang lebih baik.
Ia juga banyak memberikan penguatan tentang nilai-nilai toleransi dan perdamaian. Dengan begitu, anak-anak akan ikut berperan dalam menghargai dan menghormati orang-orang yang berbeda, baik dari segi agama maupun suku. Anak-anak juga dapat menyuarakan nilai-nilai perdamaian di mana pun mereka tumbuh besar kelak.
Ambon 2005, Pasca Relokasi dan Rekonsiliasi
Setelah proses relokasi pada tahun 2005, LAPPAN tetap fokus dalam melakukan pendampingan dan pemberdayaan bagi perempuan dan anak-anak. Salah satunya adalah dalam penanganan dan pencegahan kekerasan seksual di daerah Waringin. Dulu di wilayah tersebut memiliki angka perkawinan anak yang sangat tinggi. Namun, berkat pendampingan yang dilakukan oleh Bai bersama LAPPAN, saat ini tidak ada lagi terjadi pernikahan anak. Orang tua kini memilih menyekolahkan anak-anak mereka hingga perguruan tinggi.
Begitu juga untuk kasus kekerasan seksual yang sebelumnya tinggi, namun saat ini telah mengalami penurunan, Ini disebabkan oleh upaya ibu-ibu di wilayah tersebut dalam memberlakukan sanksi sosial kepada para pelaku dan mendorong penanganan kasus secara hukum.
Sanksi sosial diberikan dalam bentuk seperti pencopotan jabatan pelaku jika ia memiliki jabatan di komunitas, contohnya sebagai ketua RT. Selain itu, sanksi dapat berupa kewajiban membersihkan rumah ibadah dan tidak memberikan ruang bagi pelaku. Selain memberlakukan sanksi, ibu-ibu juga terus memberikan penguatan kepada korban. Mereka mengajak korban untuk tetap terlibat dalam kegiatan sosial dan keagamaan, sebagai bentuk dukungan dan pemulihan bagi korban.
Pelaku juga diberikan peringatan bila kedapatan melakukan kekerasan fisik atau lainnya terhadap istrinya. jika istrinya tidak melapor, masyarakatlah yang akan melaporkan dan memenjarakannya. Ternyata, pemberian sanksi sosial ini lebih efektif, sehingga di Waringin, orang-orang menjadi takut untuk melakukan kekerasan karena dianggap sebagai perilaku memalukan.
Dulu, banyak lembaga adat yang menyelesaikan kasus kekerasan seksual maupun KDRT di tingkat komunitas. Namun, Bai bersama LAPPAN melakukan banyak diskusi dan memberikan penguatan kelembagaan adat. Awalnya agak berat, seperti yang ia rasakan di kampung halamannya di Desa Pelauw. Di sana, angka perceraian sangat tinggi dan orang selalu bercerai secara agama di masjid.
Bai lantas mengumpulkan semua penghulu dan tokoh adat untuk memberikan penguatan bahwa yang memiliki kewenangan untuk membatalkan pernikahan adalah pengadilan. Karena itu, jika ada masyarakat yang ingin bercerai, sebaiknya mereka didorong untuk mengajukan gugatan ke pengadilan agama. Pengadilan agama akan mengeluarkan akta perceraian sebagai hasilnya.
Dalam pertemuan tersebut, Bai juga menyampaikan bahwa dalam proses adat, terkadang tidak ada ruang bagi perempuan untuk bersuara. Hal ini disebabkan karena perempuan sudah diwakili oleh saudara kawinnya, sehingga mereka tidak dapat secara langsung menyuarakan hak-hak mereka. Berbeda dengan di pengadilan, di sana perempuan dapat menyuarakan hak-haknya dan hadir dalam proses persidangan. Bai memperkuat Pemahaman ini selama periode 2007 hingga 2008. Akibatnya, saat ini orang tidak hanya bercerai secara adat, tetapi juga mengurus ke pengadilan agama atau menghubungi LAPPAN.
Begitu juga dengan kasus perkosaan. Dalam proses penyelesaian adat, Bai selalu menanyakan kepada keluarga korban, “Apakah keputusan ini dirasakan adil atau tidak?” Jika mereka menyatakan bahwa keputusan tersebut tidak adil, Bai kemudian menjelaskan bahwa terdapat alternatif hukum yang dapat diakses korban. Korban memiliki hak untuk mencari keadilan melalui jalur hukum formal.
Dengan cara itu, Bai tidak pernah menyatakan bahwa proses hukum adat itu salah. Karena hukum adat memang ada di tingkat masyarakat, sangat dihormati, dan mudah diakses. Selain itu, penanganannya juga sangat cepat, meskipun tidak selalu berpihak pada korban. Apa yang dilakukan Bai adalah memberikan pemahaman kepada tokoh-tokoh adat maupun perangkat-perangkatnya bahwa jika proses penyelesaian adat tidak memberikan efek jera kepada pelaku, hal itu sama dengan membiarkan impunitas. Dengan demikian, pelaku dapat kembali melakukan kejahatan terhadap anak-anak yang lainnya.
Penyelesaian adat sering kali dianggap sudah adil bagi korban padahal sebenarnya tidak adil dan malah merugikan dan mendiskriminasi mereka. Namun, Bai memilih jalan negosiasi dan diskusi untuk membangun pemahaman. Sehingga ketika terjadi kasus lagi, perangkat adatnya kadang-kadang langsung merujuk pada penyelesaian secara hukum formal.
Namun di beberapa daerah seperti Tanimbar dan Kei, adat masih sangat kental. Oleh karena itu Bai terus meningkatkan kapasitas perempuan di wilayah tersebut. Harapannya adalah agar ketika ada kasus, mereka dapat membedakan antara penyelesaian yang harus diselesaikan secara adat dan penyelesaian yang harus mendorong efek jera. Selain Itu, juga penting untuk memperhatikan rasa keadilan dan pemulihan bagi korban, terutama dalam kasus kekerasan berbasis gender, khususnya kekerasan seksual.
Masyarakat di Tual memiliki sistem hukum adat Larvul Ngabal. Dalam Pasal 4 dan 5 hukum adat ini, terdapat ketentuan yang mengatur tentang kesusilaan dan perlindungan perempuan. Meskipun adat memiliki pengaruh yang kuat, namun jaringan perempuan di sana terus menerus menyuarakan keadilan bagi korban. Mereka aktif mendorong kasus-kasus tertentu tidak diselesaikan melalui sidang adat, melainkan melalui mekanisme yang lebih tepat.
Meskipun terdapat pasal yang mengatur perlindungan perempuan dalam hukum adat, implementasinya tidak selalu sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan oleh adanya keterkaitan antara pelaku kekerasan seksual dengan tokoh adat atau pemerintah desa/ohoi. Namun, jaringan perempuan di Kota Tual terus menyuarakan hak-hak mereka sehingga beberapa kasus mulai dirujuk ke sistem hukum formal.
Bai melihat bahwa penanganan kasus dengan hukum adat, dalam bentuk apapun, sangatlah tidak adil. Dalam hukum adat tersebut disebutkan bahwa laki-laki yang telah membuka baju perempuan dan melakukan keasusilaan akan membayar ganti rugi. Ganti rugi dapat berupa denda piring emas atau emas, atau misalnya baju putih karena ia membuat kesucian perempuan menjadi hilang. Namun, denda adat tersebut seringkali tidak dirasakan oleh korban karena diserahkan kepada orang lain, seperti orang tua atau omnya, atau orang-orang yang memiliki hubungan dengan korban.
Bai hajar pernah mendampingi korban perkosaan di daerah Seram. Korban mengungkapkan kekecewaannya karena ia sama sekali tidak menerima ganti rugi adat yang diberikan kepadanya.
“Kenapa saya merasa kecewa ketika kakak-kakak saya meminta agar kasus pemerkosaan oleh orang ini diselesaikan secara adat? Setelah dia membayar ganti rugi sebesar 15 juta, kakak-kakak saya dan orang tua saya yang menikmati uang tersebut. Saya sama sekali tidak mendapatkan bagian apapun,” ucap korban seperti yang disampaikan Bai.
Waktu itu Bai bertanya kepada ibu korban mengenai uang tersebut. Ibu korban menjawab bahwa itu adalah uang yang tidak halal, dan korban tidak boleh mengambil manfaat dari uang tersebut. Bai mengungkapkan, “Tapi mengapa ibu dan kakak-kakaknya harus menikmati uang yang tidak halal tersebut, padahal itu menyakiti dia.” ujarnya.
Meskipun pada saat itu kasus telah diselesaikan melalui proses adat, Bai tetap mendorong penyelesaian secara formal. Akhirnya, pelaku dijatuhi hukuman penjara selama 15 tahun.
Tokoh-tokoh adat perlu diberikan penjelasan secara komprehensif. Bai memilih untuk mengumpulkan para tokoh adat dan berunding serta berdiskusi Hal yang paling penting adalah tidak menyalahkan hukum adat dan menekankan bahwa tindakan pelaku melanggar hukum dan merugikan orang lain, bahkan merendahkan harkat dan martabat seseorang.
“Jika kita tidak berjuang untuk melindungi hak-hak korban, tidak mendorong mereka untuk bersuara dan mengungkapkan kejahatan yang mereka alami, maka kasus ini akan mengalami impunitas. Pelaku akan merasa terbebas dari hukuman. Sehingga dia akan merasa bahwa tindakan yang dia lakukannya tidak akan ditindaklanjuti secara hukum, dan kemungkinan akan melakukan kejahatan serupa terhadap orang lain.” Ujar Bai.
Bai menegaskan bahwa dalam situasi tersebut, tanpa disadari kita telah melindungi para pelaku kejahatan atau kejahatan yang ada di sekitar kita. Di sisi lain, kita juga membuat orang-orang yang terluka harus hidup dalam situasi sulit dan trauma, serta menciptakan ketidakadilan. Melalui proses diskusi yang berkelanjutan dengan tokoh adat, akhirnya mereka mulai menyadari hal ini. Mereka juga sampai pada pemahaman bahwa, “Ya, memang hukum adat harus berkembang mengikuti perkembangan situasi saat ini.” Jelas Bai.
Dari segi pemimpin agama, Bai merasa tidak menghadapi tantangan yang signifikan. Hanya saja dari sisi perspektif mereka masih ada bias yang terjadi. Untuk menghadapinya, Bai memilih mendiskusikan dan menjadi teman berbincang dengan mereka. Selain itu, Bai juga melibatkan mereka dalam pendampingan kasus-kasus. Melalui proses ini, terkadang mereka mengalami perubahan seiring dengan munculnya empati terhadap persoalan yang dihadapi oleh korban.
“Jadi, pada akhirnya dia akan refleksi sendiri. Karena jika kita langsung mengatakan, ‘Mengapa anda melarangnya bercerai ketika dia telah menderita sementara sementara kondisinya sudah buruk dan tersiksa?’ itu tidak mungkin. Tetapi kita akan mengajak mereka untuk mendampingi dan memperkuat. Korban bersama-sama. Di sinilah perspektif mereka mulai berubah. Mereka mulai berpihak pada korban dan tidak lagi menyalahkan. Mereka akan mendukung keputusan korban apapun karena menurut mereka itu adalah pilihan terbaik.” ujarnya.
Selama proses pendampingan, tidak sedikit korban KDRT dan kekerasan seksual mengalami akhir yang tragis. Pada tahun 2022, tercatat ada 3 korban KDRT yang meninggal dunia, demikian pula dengan korban kekerasan seksual mencapai 3 orang. Sementara itu, jumlah kasus yang dilaporkan di kota Tual pada tahun 2022 mencapai 50 kasus. Di wilayah Maluku Tenggara, terdapat 21 kasus yang tercatat, dengan 11 kasus kekerasan seksual dan 10 kasus KDRT.
Bai mengkhawatirkan bahwa kondisi perempuan semakin memburuk dan berpotensi berdampak pada kasus kematian. Oleh karena itu, ia merasa perlu membuka komunikasi dengan lembaga keagamaan, pemerintah desa sampai ke level RT. Tujuannya adalah menciptakan mekanisme dan ruang aman bagi perempuan dan anak-anak.
Dalam melaksanakan tugasnya di wilayah geografis Maluku Bai mengakui bahwa ia menghadapi sejumlah kendala dan keterbatasan. Terutama di daerah pegunungan yang masih terisolasi, ia mengalami kesulitan dalam mengakses korban di lokasi tersebut. Untuk menjangkau wilayah tersebut, ia harus melewati berjalan kaki beberapa kilo dan membutuhkan waktu beberapa hari.
Sementara itu, kondisi korban sangat memprihatinkan. Mereka tinggal di rumah yang tidak layak huni, tanpa akses listrik atau penyinaran yang memadai. Orang tua atau keluarga korban juga tidak mampu berkomunikasi dalam bahasa Indonesia. Bai dan pendamping komunitasnya juga menghadapi kesulitan dalam membawa korban yang sedang hamil untuk pemeriksaan USG dan mengakses layanan kesehatan yang diperlukan.
Seperti pengalamannya saat kunjungan ke Imabatai, Bai dan pendamping komunitas menghadapi kendala dalam membawa korban yang sedang hamil. Desa tersebut terletak sejauh 20 Km dari puskesmas terdekat, dengan kondisi jalan yang buruk.
“Saat saya bertanya mengenai ibu-ibu hamil dan ibu-ibu yang akan melahirkan, mereka menjawab bahwa ada dukun yang dapat membantu,” ujar Bai. Sementara itu, korban dalam kondisi kritis dan harus segera dibawa ke puskesmas di Kairatu yang jaraknya sangat jauh. Namun sayangnya, sang bayi tidak dapat diselamatkan dan meninggal dunia, sementara korban berhasil selamat.
Bai juga menghadapi tantangan berat saat mendatangi korban di daerah Mange-Mange. Korban perkosaan ini berusia 12 tahun, sedang dalam kondisi hamil, dan keluarganya tidak memiliki biaya untuk pengobatan karena hidup dalam kemiskinan.
“Akhirnya kami datang dan membawa anak tersebut untuk menjalani pemeriksaan kesehatan di Ambon, bertemu dengan dokter kebidanan. Setelah menjalani USG, usia kehamilannya sudah mencapai tujuh bulan, tetapi berat janinnya tidak mencukupi. Jadi kami harus konsultasi untuk memberikan asupan gizi yang tepat agar anak ini dapat melahirkan bayi yang dengan berat yang sesuai. Akhirnya, dia melahirkan dengan berat bayi sebesar 2 Kg,” jelasnya.
Sementara itu, proses hukum tetap berjalan dan LAPPAN terus mendampingi korban meskipun menghadapi kondisi geografis yang sulit. Belum lagi masalah cuaca ekstrem yang menjadi kendala tambahan. Misalnya, wilayah Seram Bagian Timur yang harus dijangkau dengan speedboat, itupun tidaklah mudah terutama ketika cuaca sedang tidak mendukung. Begitu juga dengan wilayah-wilayah kepulauan yang memerlukan biaya yang tinggi untuk dapat mencapainya. Ditambah lagi, kondisi cuaca yang tidak bisa diprediksi juga menjadi faktor yang mempengaruhi. Terdapat satu kejadian di mana korban harus pergi ke Ambon untuk persidangan, namun disebabkan cuaca buruk, LAPPAN harus menghubungi jaksa dan hakim meminta penundaan sidang karena cuaca tidak memungkinkan bagi korban dan saksi-saksi untuk menyeberang.
“Terkadang kita sudah sampai di pulau A. Begitu hendak menyeberang ke Pulau B untuk menemui korban, cuaca di sana sedang buruk. Hal ini sering menjadi kendala, terutama jika mereka harus datang untuk proses persidangan.” terang Bai.
Korban yang berada di wilayah terpencil, terisolir dan terluar juga menghadapi kendala dalam berkomunikasi dan mengakses informasi. Bai menghadapi kesulitan untuk menghubungi dan berkomunikasi lewat telepon seluler. Di beberapa daerah, jaringan tersedia sehingga komunikasi bisa berjalan lancar, namun di beberapa daerah lainnya kondisi jaringannya tidak baik, sehingga komunikasi menjadi sulit.
Bai telah berupaya melakukan koordinasi dengan Dinas Kominfo untuk menyediakan saluran informasi dan komunikasi di wilayah-wilayah sulit dijangkau agar masyarakat dapat mengakses informasi dan berkomunikasi. Namun, tindak lanjut dari koordinasi tersebut belum ada. Ketimpangan pembangunan menyebabkan kondisi korban menjadi semakin rentan dan sulit mendapatkan hak-haknya. Faktor-faktor seperti minimnya infrastruktur jalan, terbatasnya sarana telekomunikasi, dan ketiadaan listrik menjadi tantangan dalam upaya penanganan korban kekerasan seksual.
Tidak jarang korban dan saksi menghadapi ancaman dari pelaku. Hingga saat ini, hanya Kota Ambon yang memiliki rumah aman, sedangkan Kabupaten/kota lainnya belum menyediakan fasilitas serupa. Di beberapa kota/kabupaten, biaya visum masih dibebankan pada korban, contohnya Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Seram Bagian Timur. Beruntungnya polisi dapat memberikan dukungan dengan menyediakan biaya visum untuk membantu proses tersebut.
LAPPAN memfasilitasi kebutuhan transportasi korban, mulai dari proses pelaporan ke kepolisian hingga persidangan mengingat korban rata-rata berasal dari keluarga miskin. Beberapa pemerintah kabupaten kecuali Kabupaten Buru, Kabupaten Kota Ambon, Kabupaten Maluku Tengah dan Kota Tual, telah mengalokasikan anggaran dalam APBD mereka untuk membiayai transportasi korban. Mereka berperan dalam memfasilitasi transportasi bagi korban.
Layanan P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) belum tersedia di semua wilayah, termasuk di Maluku Tengah, Seram Bagian Barat (SBB), dan Seram Bagian Timur (SBT). Akibatnya, tidak tersedia anggaran yang khusus untuk mendukung, yang menyebabkan kesulitan dalam penyediaan layanan oleh LAPPAN dan kepolisian.
“Misalnya, dalam kasus di SBT, korban mengalami perkosaan oleh ayah tirinya. Ketika hakim hendak memberikan putusan, ibu kandung korban menangis dan tidak ingin pelaku dipenjara karena ia secara ekonomi bergantung pada suaminya. Akhirnya, anaknya diusir dari rumah. Namun, di wilayah tersebut tidak ada rumah aman yang tersedia. Anak tersebut kemudian disalahkan oleh orang lain, sampai dia trauma dan merasa bersalah. Akhirnya, dia ditempatkan di rumah salah seorang jaksa,” ujar Bai.
LAPPAN pernah menjalin kerjasama dengan Fakultas Psikologi UI untuk memberikan penguatan pada korban dan keluarga mereka. Salah satu kasus terjadi di wilayah SBT, di mana seorang anak menjadi korban pemerkosaan oleh gurunya. Proses hukum berjalan hingga pelaku dipenjara, namun korban mengalami trauma dan depresi berat. Bai menghadapi kesulitan karena tidak tersedia layanan di wilayah STB, sementara sumber daya LAPPAN juga terbatas. Oleh karena itu, Ia akhirnya meminta bantuan dari Fakultas Psikologi UI untuk memberikan dukungan pada korban.
“Waktu itu saya meminta bantuan teman-teman dari Fakultas Psikologi UI melalui video call, kemudian kami memberikan penguatan. Saya tinggal di wilayah tersebut selama satu minggu, memberikan dukungan kepada keluarga korban dan korban itu sendiri. Kami berupaya mengidentifikasi sumber daya yang tersedia di sekitar, termasuk melibatkan gurunya. Kami meminta agar guru tersebut dapat memberikan pemulihan kepada korban jika memungkinkan.” ungkap Bai
Upaya penguatan yang dilakukan oleh bersama LAPPAN terhadap perempuan juga melibatkan keluarga, terutama para suami. Bai menjalankan program pendidikan keluarga berwawasan gender. Program ini diimplementasikan di masyarakat perkotaan di Kota Ambon yang menghadapi tantangan kepadatan penduduk, kondisi ekonomi yang sulit, dan tingkat pendidikan yang rendah.
“Jadi jika istri sibuk bekerja atau aktif di Posyandu, Suami dapat membantu melakukan kerja-kerja domestic. Penting untuk menghindari situasi di mana istri sibuk, sedangkan suami pulang dalam keadaan mabuk dan melakukan kekerasan terhadap istri yang berdampak sangat merugikan istri dan keluarga. Akhirnya, para suami yang sebelumnya enggan melakukan pekerjaan rumah, mulai mau mencuci, mengangkat air, dan membersihkan rumah. Mereka juga mulai mengantar anak-anak pergi sekolah.” terangnya. Bai menyampaikan kepada para suami: “Kasihan itu mama-mamanya, semua beban diberikan kepada mama, sampai mereka tidak punya waktu untuk istirahat”.
Sementara pada mama-mama, Bai mengatakan, “Jangan pernah berpikir bahwa setelah menikah tubuh kita menjadi milik suami. Menikah hanya untuk mendapatkan legalitas agama dan hukum. Tubuh kita adalah milik kita sendiri, properti pribadi kita. Ketika kita merasa bahwa tubuh kita adalah milik suami, dan jika suami menampar atau memukul kita, kita mungkin menganggapnya sebagai didikan atau sesuatu yang baik. Padahal, itu sangat menyakitkan dan melanggar hak asasi kita. Jangan biarkan tubuh menderita dan akhirnya menjadi cacat, bahkan yang lebih fatal, nyawa kita terancam atau hilang karena kekerasan”.
Ambon 2023, Menatap Masa Depan
Kerja keras Bai memberdayakan perempuan dan anak serta mendorong perubahan di komunitas akhirnya membuahkan hasil. Pada tahun 2012, Bai dianugerahi penghargaan Saparinah Sadli. Penghargaan ini diberikan kepada perempuan yang gigih dalam mempromosikan isu-isu Hak Asasi Manusia (HAM). Nama penghargaan ini diambil dari seorang aktivis perempuan senior yang mendirikan Program Studi Kajian Gender di Universitas Indonesia dan turut berperan dalam membidani lahirnya Komnas Perempuan.
Pada tahun 2013 Bai juga mendapat penghargaan Indonesian Women of Change Award dari Pusat Kebudayaan Amerika. Baihajar berhasil memenangkan penghargaan dalam kategori Demokrasi dan Masyarakat Madani.
Pada tahun 2022, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual disahkan setelah lebih dari 10 tahun perjuangan. Aktivis perempuan memandang pengesahan UU ini sebagai tonggak penting dalam upaya penanganan dan pencegahan kekerasan seksual. Namun, ada pekerjaan rumah yang menanti terkait implementasinya di lapangan.
Setelah melewati proses yang panjang selama lebih dari dua dekade dalam mendampingi perempuan korban kekerasan seksual, Baihajar masih menyimpan mimpi. Ia berharap pemberdayaan perempuan dapat dilakukan secara merata, menjangkau wilayah pulau-pulau kecil terluar dan daerah-daerah yang terisolasi. Baihajar ingin menyediakan layanan dengan pendekatan berbasis kepulauan agar mudah dijangkau oleh korban.
Dengan demikian, hak-hak korban dapat terpenuhi, terutama hak atas pengungkapan kebenaran, keadilan dan pemulihan.